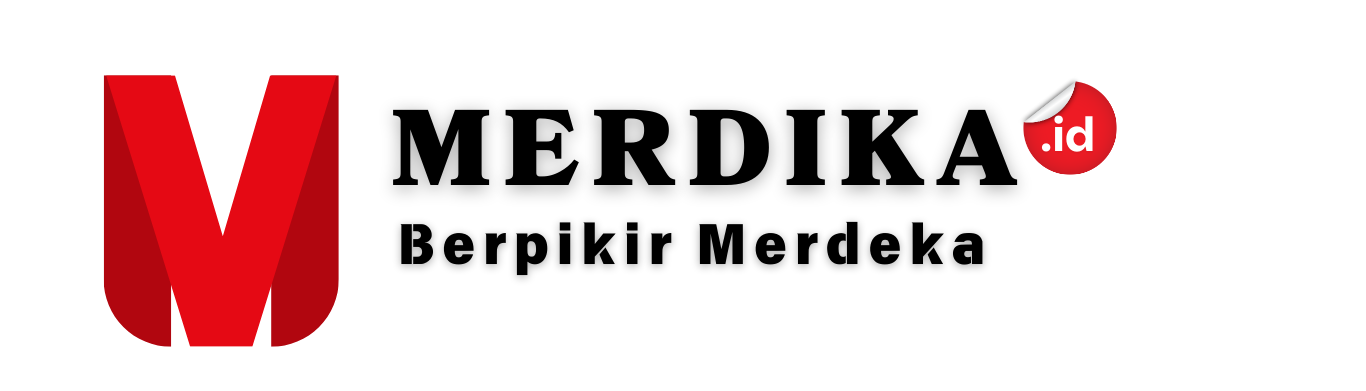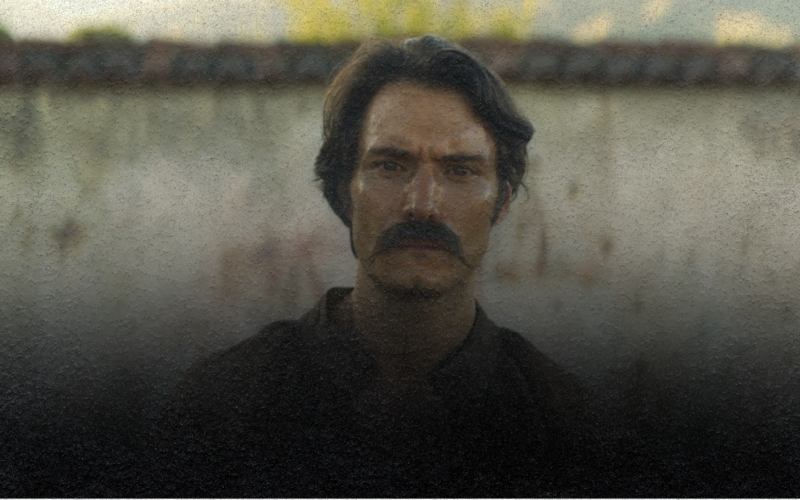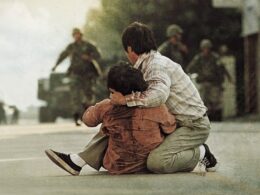Setiap karya seni tidak bisa terpisah dari keadaan yang melatarinya. Karena itu, keadaan yang meliputi kehidupan rakyat, entah sedang susah maupun senang, akan tercermin dalam kesenian.
Begitu pula ketika rakyat mengalami situasi ketertindasan. Pada saat itu pula, kesenian bisa menjadi medium untuk menyampaikan pesan-pesan perlawanan. Saya kira, bangsa Indonesia punya banyak sekali kesenian rakyat berbau perlawanan. Lenong adalah salah satunya.
Cuplikan sejarah lenong
Lenong adalah seni teater rakyat yang hidup di masyarakat Betawi. Banyak sejarahwan memperkirakan, seni teater rakyat ini sudah muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Ada yang bilang, lenong hanyalah hasil teaterisasi dan pengembangan musik gambang kromong. Gambang kromong adalah sejenis orkes yang memadukan gamelan dengan alat musik Tionghoa, seperti sukong, tehyan, dan kongahyan.
Versi lainnya berpendapat, lenong berasal dari pengembangan wayang Abdul Muluk. Kesenian itu sudah dikenal di Sumatera sejak 1886, yang dipengaruhi oleh komedi Parsi dan wayang Tiongkok. Wayang Abdul Muluk masuk Jakarta sekitar 1910-an. Nama lenong sendiri muncul pada tahun 1920-an. Pada saat itu, musik pengiringnya adalah gambang kromong.
Namun, menurut sejarahwan Betawi, Alwi Shahab, kelahiran lenong tidak bisa dipisahkan dipisahkan dari perlawanan diam-diam terhadap sistem tanam-paksa (cultuurstelsel). Namun, perlawanan ini mulai meletus ketika diterapkan sistem tanah partikulir (swasta). Akibatnya, tanah-tanah milik rakyat dirampas oleh penguasa kolonial dan kaum kaya. Sementara rakyat, yang sudah tidak punya tanah, dipaksa bekerja di tanah partikulir itu. Sudah begitu, rakyat dibebani pajak dan kerja-paksa.
Penindasan itu melahirkan perlawanan. Terjadi pemberontakan rakyat di mana-mana, seperti pemberontakan Cikandir (1836), peristiwa Cikandi-Udik (1845), dan peristiwa Tambun. Dari situ juga lahir tokoh-tokoh pemimpin perlawanan rakyat, seperi Si Pitung, Si Jampang, dan Entong Gendut.
Dulu lenong dipertunjukkan melalui “ngamen” dari kampung ke kampung. Pertunjukan dilakukan di alam bebas, tanpa panggung. Pada saat pertunjukan berlangsung, ada pemain yang ditugaskan mengitari penonton sembari meminta sumbangan.
Dalam perkembangan selanjutnya, lenong mulai mengisi acara-acara hajatan dan perkawinan. Lalu, seusai proklamasi kemerdekaan, lenong muncul sebagai teater rakyat di atas panggung.
Lenong sendiri ada dua jenis, lenong dines/denes dan lenong preman. Lenong dines mengangkat kisah raja-raja atau bangsawan. Kalau mentas, pemainnya menggunakan kostum resmi. Bahasa yang digunakan pun bahasa resmi atau melayu tinggi.
Berbeda dengan lenong dines, lenong preman justru mengangkat kehidupan rakyat sehari-hari. Cerita yang diangkat pun adalah cerita-cerita perlawanan rakyat. Kostumnya mengikuti rakyat kebanyakan. Selain itu, lenong preman lebih suka menggunakan bahasa rakyat jelata.
Dalam perkembangannya, lenong dines nyaris punah, sedangkan lenong preman masih bertahan. Meskipun demikian, akibat gempuran budaya barat, lenong preman pun mulai redup.
Humor dan ungkapan protes
Yang menarik dari lenong adalah humor atau banyolannya. Sampai-sampai ada ungkapan: lenong tanpa humor seperti sayur tak berbumbu. Apalagi, masyarakat Betawi sangat akrab dengan humor.
Namun, jangan salah, humor itu bukan tanpa makna. Pada zaman itu, humor merupakan bentuk “pelepasan” dari segala tekanan. Dengan tertawa, orang bisa sedikit lepas dari tekanan.
Antropolog James Danangdjaja mengatakan, humor merupakan sarana efektif bagi seorang pemain teater untuk melancarkan kritik. Sedangkan menurut sejarahwan Sartono Kartodirdjo, sindiran merupakan ungkapan hati nurani rakyat yang terpendam.
Dalam lenong, humor itu terletak di dialog antar pemain dan adegan, bukan pada alur cerita. Dengan kepatuhan pada alur, setiap pemain tidak lepas dari tujuan cerita yang diangkat. Humor itu, misalnya, diungkapkan seolah-olah tidak sengaja alias keseleo lidah.
Tak hanya itu, cerita-cerita yang diangkat dalam lenong adalah pahlawan-pahlawan rakyat, seperti Si Pitung, Si Jampang, Ayub Jago Betawi, Nyai Dasima, dan lain-lain. Akan tetapi, lenong juga terkadang mengungkit kehidupan rakyat sehari-hari.
Pemain lenong sendiri dituntut punya keahlian. Maklum, dialog yang dipentaskan jarang mengacu pada skenario, melainkan kemampuan improvisasi pemainnya. Dengan begitu, kritik sosial yang dilontarkan bisa mengacu pada situasi aktual.
Sebagai teater rakyat, lenong bisa efektif sebagai senjata perlawanan. Lagi pula, pertunjukan lenong pun bisa jadi ajang mobilisasi massa. Dengan begitu, lenong bisa menjadi sarana edukasi politik dan penyadaran bagi massa-rakyat.