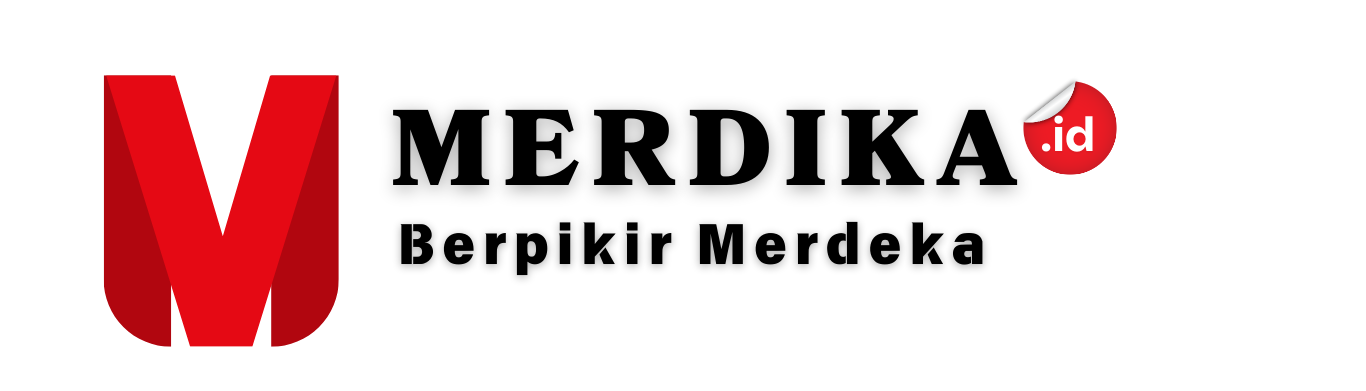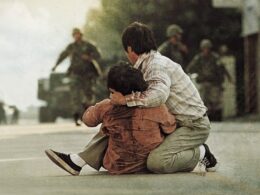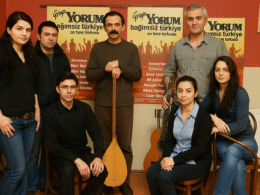Kakanda, dari zaman berganti zaman.
Tatap hatiku menanti tuan.
Kakanda bakal membawa merdeka.
Sebab tjintamu kepada loka.
Itulah sebait naskah drama “Bebasari” karya Roestam Effendi. Drama ini bercerita tentang pemuda yang hendak merebut kekasihnya, Bebasari, yang direnggut Rahwana. Roestam Effendi, seorang aktivis komunis, berusaha mengadaptasi cerita Ramayana dalam konteks penindasan kolonial di Indonesia.
Cerita Bebasari ini sering dipentaskan melalui wayang. Bebasari melambangkan cita-cita kemerdekaan. Sedangkan Rahwana merupakan simbol penjajah alias kolonialisme. Sedangkan Bujangga, tokoh utama, melambangkan pemuda yang sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan.
Itulah bukti betapa wayang, yang ceritanya diadaptasi sesuai keadaan, sanggup menjadi media untuk membangkitkan perlawanan. Dengan demikian, wayang bukan sekadar seni pertunjukan, tetapi juga bagian dari catatan perlawanan itu sendiri.
Sepintas sejarah
Wayang punya sejarah panjang dalam masyarakat Indonesia. Beberapa pendapat mengatakan, wayang sudah dikenal bangsa Indonesia sejak 1500 SM. Artinya, masyarakat Indonesia sudah mengenal wayang jauh sebelum pengaruh Hindu (India).
Sumber lain menyebutkan, wayang sudah dikenal sejak Airlangga, yang berkuasa pada abad ke-10. Lalu, ada pula yang mengatakan, wayang diciptakan oleh Raja Jayabaya dari Kediri, sekitar abad ke-10, ketika berusaha mengabadikan wajah leluhurnya melalui gambar. Inilah cikal bakal wayang purwa.
Dua orang peneliti, N.J. Krom dan W. Rassers, menganggap pertunjukan wayang di Jawa sama dengan pertunjukan serupa di India barat. Dengan demikian, wayang dianggap perpaduan kebudayaan Jawa dan India.
Ada lagi yang berpendapat, seperti G. Schlegel, bahwa wayang sudah muncul di Tiongkok di era pemerintahan Wu Ti (kira-kira 140 SM). Konon, wayang ini berasal dari seni pertunjukan bayang-bayang.
Musyawarah pewayangan 1965 menyimpulkan, sejarah pewayangan di Indonesia dimulai kira-kira sejak tahun 800 Masehi. Katanya, wayang muncul sebagai kegiatan sastra dengan juru-juru dongen yang disebut “Juru Barata”.
Pada tahun 1583, wayang tampil sebagai hiburan rakyat yang bersifat cair dan egaliter. Sejak itu, wayang menjadi populer di kalangan rakyat Indonesia. Pementasan wayang berlangsung di kampung-kampung. Namun, seiring dengan proses itu, kaum feodal berusaha mengkooptasi wayang demi kepentingannya.
Sejak itulah wayang banyak dipengaruhi mistisisme. Cerita-cerita wayang juga banyak dipengaruhi unsur-unsur feodal.
Wayang pun berkembang dengan berbagai jenisnya: wayang Purwa (cerita-cerita Ramayana dan Mahabrata), wayang Madya (cerita Prabu Parikesit), wayang gedog atau topeng (walisongo), wayang Wasana (Kerajaan Majapahit), dan wayang Suluh atau wayang Pantjasila.
Dalam kancah perjuangan
Dalam derap langkah revolusi Indonesia, kesenian wayang juga menyetor andil. Kisah Roestam Effendi dan naskah Bebasari-nya adalah salah satu contoh. Ada banyak contoh lain yang mengungkap hal itu.
Pada November 1947, pada sebuah kongres pemuda di Madiun, Jawa Timur, disepakati wayang sebagai sarana propaganda. Inilah yang melahirkan kesenian wayang yang disebut “wayang suluh”. Suluh berarti penerangan, pencerahan, atau pembebasan pemikiran rakyat.
Wayang suluh dibuat dari kulit, tetapi sosoknya mengambil tokoh-tokoh pergerakan, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Amir Sjarifuddin, Diponegoro, dan lain-lain. Tema yang diangkat oleh wayang ini adalah tema-tema perjuangan.
Pasang politik revolusi 1945 hingga 1960-an sangat berpengaruh pada kesenian wayang. Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), salah satu organisasi kebudayaan kiri, berusaha melakukan pembaruan pada kesenian wayang, terutama pada isi dan bentuknya.
Lekra berusaha meruntuhkan “pakem-pakem” feodal dalam kesenian wayang. Cerita-cerita yang menggambarkan kehidupan feodal ditanggalkan. Sebaliknya, para dalang didorong untuk mengangkat kisah-kisah aktual dan nyata di tengah rakyat. Nama-nama tokoh juga terkadang diubah sesuai kebutuhan.
Kisah Ramayana, misalnya, dikembangkan dengan kebutuhan di zaman itu. Digambarkan bahwa kisah Ramayana menyangkut pertentangan dua kekuatan, yakni Rama dengan kekuatannya rakyat kera melawan Rahwana. Rama merupakan representasi kekuatan rakyat, sedangkan Rahwana mewakili kekuasaan lalim.
Seiring dengan itu, muncul upaya untuk “meng-indonesia-kan” kesenian wayang. Sejumlah kelompok pewayangan mulai menggunakan bahasa Indonesia. Komik-komik berisi cerita wayang diterbitkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dharma Budaya, sebuah kelompok pewayangan dari Yogyakarta, berusaha menerobos batas kesukuan agar wayang menjadi kebudayaan rakyat Indonesia.
Media protes sosial
Pada tahun 2003, wayang dinobatkan oleh UNESCO sebagai maha-karya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Dengan demikian, wayang dapat dianggap sebagai sumbangan bangsa Indonesia terhadap kesenian dunia.
Namun, tugas wayang bukan sekadar menghidangkan hiburan. Sebagai kebudayaan rakyat, wayang tidak bisa terpisah dari keadaan sosial yang melingkupi rakyat. Karena itu, wayang bisa menjadi penyalur atau ekspresi sosial.
Sejarah membuktikan, wayang bisa ditumpangi oleh berbagai pesan dan kritik-kritik sosial. Belakangan, banyak aksi protes yang menyertakan wayang sebagai medium menyampaikan pesan protesnya.
Kesenian rakyat juga dituntut terbuka terhadap perkembangan zaman. Jika tidak, mereka tentu akan ditinggalkan generasi muda. Untuk itu, upaya melakukan terobosan dalam kesenian wayang patut diapresiasi.
Belakangan muncul wayang hip-hop, yang berusaha memadukan antara kesenian wayang dengan musik hip-hop. Kelahiran wayang hip-hop memang menuai pro-kontra. Sebagian berpandangan, wayang hip-hop telah melabrak tradisi dan mendegradasi nilai-nilai filosofis-moral wayang asli. Sebaliknya, pendukung wayang hip-hip menyerukan perlunya kesenian wayang mengadaptasi semangat zaman.
Terlepas dari kontroversi itu, ada satu hal yang tak bisa dilupakan: melestarikan kesenian wayang sebagai kebudayaan rakyat!