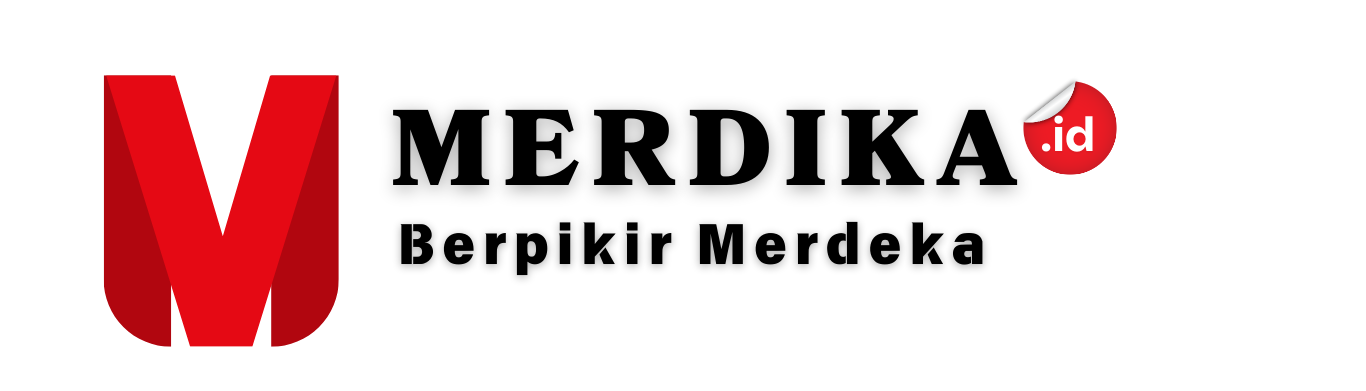Di tengah gelapnya feodalisme dan kolonialisme, dia berani bersuara tentang satu hal yang paling ditakuti penguasa: pendidikan untuk semua. Dia adalah Kartini.
Kartini hidup dalam dunia yang percaya bahwa lahir sebagai perempuan adalah kutukan, bahwa jadi pribumi berarti tak perlu sekolah tinggi, dan bahwa kemajuan hanyalah milik segelintir elite.
Tapi dari balik dinding pingitan, Kartini membaca, menulis, dan menggugat. Ia melihat pendidikan bukan sekadar soal angka dan ijazah, melainkan pintu menuju kemerdekaan pikiran. Sebuah jalan sunyi yang pelan-pelan bisa mengubah nasib suatu bangsa.
Kartini mengumpamakan rakyat Hindia-Belanda kala itu seperti “rimba belantara” yang gelap gulita. Untuk meneranginya dibutuhkan obor. Dan, obor itu adalah ilmu pengetahuan.
Kartini meletakkan pendidikan sebagai kunci emansipasi.. Dengan pendidikan, seseorang bukan saja bisa mengejar kemajuan, tetapi jiwa dan pikirannya juga turut merdeka.
“Kalau orang Jawa berpengetahuan, ia tidak akan lagi mengiyakan dan mengamini saja segala sesuatu yang ingin dikatakan atau diwajibkan oleh atasannya,” tulis Kartini kepada E.H. Zeehandelaar, 12 Januari 1900.

di Bogor . Kredit: Tropenmuseum
Lantas, bagaimana gagasan Kartini tentang mencerdaskan kehidupan bangsa?
Pertama, pendidikan untuk semua. Sebagai kunci kemajuan, pendidikan yang berkualitas harus bisa diakses oleh seluruh rakyat, tanpa memandang suku, agama, gender, dan status sosialnya.
Pada masa Kartini, pendidikan masih menjadi “privilege” bagi kaum elite, terutama keturunan Belanda/Eropa dan kaum bangsawan. Europeesche Lagere School (ELS), misalnya, yang berdiri sejak 1817, hanya menerima murid dari keturunan Belanda. Baru di tahun 1903, karena dobrakan politik etis, sekolah ini membuka pintu bagi pribumi. Begitu juga Hollandsch-Inlandsche School (HIS), yang diperuntukkan hanya untuk keturunan bangsawan dan tokoh terkemuka.
Karena itu, ketika ada pribumi yang melangkah maju dalam pendidikan, Kartini sangat mendukungnya. Kartini memuji Abdul Rivai, seorang dokter Jawa lulusan 1894, sebagai salah satu obor yang akan menerangi Hindia. Dia juga berusaha keras membantu Agus Salim―kelak dikenal akrab sebagai Haji Agus Salim, pemuda lulusan HBS, yang hendak melanjutkan pendidikan di negeri Belanda.
Kedua, pendidikan tanpa diskriminasi. Meskipun terlahir dari keluarga bangsawan, Kartini sangat menentang feodalisme, termasuk feodalisme dalam pendidikan. Dia tak setuju ada pembeda-bedaan jenis dan kualitas pendidikan bagi setiap orang berdasarkan status sosialnya.
Kartini menjelaskan pandangannya itu kepada sahabat penanya, Estella Zeehandelaar:
“…apakah yang dilakukan pemerintah buat pendidikan rakyat? Bagi putra-putra bangsawan telah ada apa yang dinamai Sekolah Raja, sekolah-sekolah guru, dan sekolah Dokter Jawa, serta sebuah sekolah pribumi di setiap distrik yang terbuka bagi setiap orang. Tetapi pemerintah telah membelah sekolah tersebut dalam dua kelas. Kelas pertama yang ada di ibu kota kabupaten dengan mata pelajaran yang sama seperti sebelum pembelahan, tetapi pada sekolah-sekolah kelas kedua hanya diajarkan bahasa Jawa dan sedikit berhitung…” (Panggil Aku Kartini Saja, 139)

Pada 1895, pemerintah Hindia-Belanda membatasi anak-anak pribumi usia 6-7 tahun untuk masuk sekolah rendah Eropa kalau tidak bisa berbahasa Belanda. Mereka tidak diterima masuk sekolah apabila tidak bisa berbahasa belanda. Sementara itu, mereka tidak memiliki kesempatan belajar bahasa Belanda.
Menurut Kartini, kaum feodal sangat berkepentingan menjadikan pendidikan sebagai hak istimewanya. Rakyat jelata tak boleh mengenyam pendidikan.
“Kaum bangsawan hendak pegang sendiri seluruh peran; dia sendiri saja yang mau pegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri, dan dia sendiri saja yang semestinya menguasai peradaban dan kemajuan Eropa,” tulis Kartini pada Estelle Zeehandelaar, 12 Januari 1900.
Bayangkan, dalam kungkungan feodalisme yang masih mencengkram kuat, Kartini sudah berseru-seru tentang kesetaraan hak dan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan.
Ketiga, pendidikan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan. Kartini yang akrab dengan Eropa lewat bacaan tahu betul bagaimana ilmu pengetahuan menggerakkan lokomotif peradaban Eropa. Dia juga yakin, ilmu pengetahuan bisa menjadi senjata penting untuk membebaskan rakyat pribumi dari pembodohan dan penindasan.
Kartini mengatakan, “Pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk mengubah pola pikir mereka, yakni penanaman kesadaran bahwa saat ini mereka tertindas, tanpa pendidikan mereka akan terus dijajah dan tidak menyadari bahwa diri mereka sebenarnya terbelenggu.” (The Chronicle of Kartini, 2010:360).
Dengan menganalogikan pendidikan seperti obor, Kartini menginginkan pendidikan tak hanya menerangi orang, tetapi menerangi banyak orang.
Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa harus seperti kata-kata Multatuli yang sangat disukai Kartini: memanusiakan manusia. Pendidikan harus mempertinggi derajat kemanusiaan.

Namun satu abad lebih sejak Kartini menulis surat-suratnya, pertanyaan besar masih menggantung di langit-langit republik ini: apakah pendidikan sudah benar-benar memerdekakan kita?
Faktanya, masih ada 2,9 juta orang Indonesia yang buta huruf (BPS, 2020). Sementara 4,08 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Kualitas pendidikan pun bagai langit dan sumur: sekolah unggulan penuh teknologi dan guru bersertifikasi hanya bisa dinikmati segelintir siswa, sementara sekolah-sekolah di pelosok masih kekurangan buku, guru, bahkan atap yang layak.
Selain itu, kualitas pendidikan kita masih tertinggal jauh dari negara-negara maju. Mengutamakan hafalan, mengekang kemerdekaan berpikir, dan menanamkan kepatuhan ketimbang keberanian berpikir. Padahal, seperti kata Kartini, ilmu seharusnya membebaskan manusia dari sekadar “mengiyakan dan mengamini” apa pun yang datang dari atas.
Kita tak kekurangan sumber daya untuk memajukan pendidikan. Tapi kita kekurangan keberanian untuk setia pada cita-cita awal bangsa: mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat, tanpa kecuali. Kartini sudah menyalakan obor itu. Sekarang, giliran kita menjaga apinya—agar tak padam di tangan generasi berikutnya.