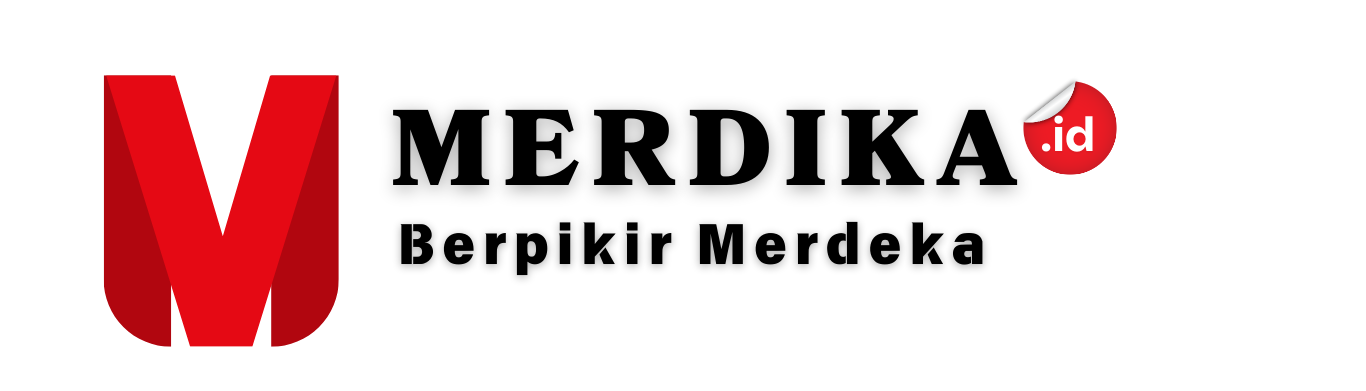Pada 2008, seorang ibu rumah tangga berkeluh-kesah soal kemungkinan salah diagnosis penyakitnya di sebuah rumah sakit swasta.
Sebetulnya, ia mengeluh lewat surat elektronik (surel) pribadi kepada teman-teman dekatnya. Namun, entah mengapa, surel itu tersebar luas di internet. Pihak rumah sakit pun keberatan dan mempolisikan ibu muda itu.
Prita Mulyasari, nama ibu muda tersebut, kemudian dipenjara. Ia menjadi korban pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Namun, kriminalisasi terhadap Prita ini viral di media sosial. Simpati dan solidaritas pun mengalir. Koin untuk Prita, penggalangan dana pertama untuk korban ketidakadilan, berhasil mengumpulkan Rp 605 juta. Melihat arus besar yang mendukung Prita, para politisi pun ikut menunggangi gelombang (riding the wave) gerakan ini.
Kasus Prita adalah kasus viral pertama lewat internet di Indonesia. Sejak itu, hampir setiap hari, kita disuguhi cerita-cerita ketidakadilan yang viral di media sosial. Para pencari keadilan, yang nyaris putus-asa keluar masuk kantor penegak hukum tanpa menuai hasil, mulai menaruh harapan pada media sosial (medsos).
Dan, memang, ketika sebuah kasus viral di medsos, barulah pemerintah dan aparat penegak hukum mulai tunggang-langgang untuk merespons masalah. Sampai-sampai muncul istilah: no viral, no justice.
Hukum dan keadilan
Hukum itu peraturan akal sehat demi kebaikan bersama, kata Thomas Aquinas. Tujuan tertinggi hukum adalah keadilan atau kebaikan bersama. Maka ada peribahasa hukum yang berbunyi: Lex iniusta non est lex (hukum yang tidak berkeadilan bukanlah hukum sama sekali).
Karena itu, ukuran bekerjanya hukum bukan sekadar hadirnya UU atau peraturan, bukan sekadar kepatuhan pada prosedur, tetapi juga soal hadirnya rasa keadilan.
Di Indonesia, masalahnya bukan hanya absennya keadilan dalam penegakan hukum, tetapi institusi penegak hukumnya sendiri mengidap banyak masalah: korup, kurang profesional, dan tidak imparsial.
Sudah jadi kebiasaan umum, orang kehilangan harta benda, seperti handphone dan kendaraan bermotor, terkadang tak mau melapor ke polisi. Selain potensi penemuan kembali barang itu sangat kecil, biaya yang dikeluarkan justru bisa membengkak. Karena itu, di media sosial sempat ramai tagar #PercumaLaporPolisi.
Mencari keadilan di Indonesia ibarat mencari jarum di tengah tumpukan jerami. Bukan mustahil, tetapi peluang mendapatkannya sangat kecil. Para pencari keadilan paling gigih sekalipun kerap berujung patah arang dan kecewa.
Kekuatan sosial media
Media sosial, yang mulai populer di Indonesia sejak 2010, punya kemampuan menghubungkan banyak manusia lintas batas teritorial. Selain itu, medsos memiliki fitur-fitur yang memungkinkan penggunanya berbagi informasi dan pengalaman secara langsung.
Dalam banyak kejadian, medsos menjadi tempat mengadu sekaligus curhat bagi para pencari keadilan. Tak sedikit yang berbagi kisah malang sebagai korban ketidakadilan, tetapi tetapi tak punya daya dan suara. Dan, medsos, dengan efek viralnya, bisa menjadi ruang untuk mencari keadilan.
Ada banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terungkap dan tertangani oleh aparat setelah viral di media sosial. Ada banyak aparat korup dan melanggar etik yang terkena sanksi setelah kasusnya viral di medsos. Bahkan, tak sedikit kebijakan pemerintah yang dibatalkan setelah ditolak dan viral di media sosial.
Dari kasus Prita Mulyasari hingga kasus Vina di Cirebon, publik semakin menyadari bahwa media sosial merupakan senjata efektif untuk mendobrak penegakan hukum yang lambat dan korup. Sehingga muncul fenomena: no viral, no justice. Viral dulu di media sosial, baru ditanggapi oleh penegak hukum.
Konsekuensi negatif
Meskipun medsos menjanjikan bisa menjadi obor untuk menerangi gelapnya penegakan hukum, tetapi ada juga konsekuensinya.
Memviralkan sebuah kasus berpotensi menyebarluaskan data pribadi seseorang dan bisa berpotensi serangan balik. Perlu diketahui, pengungkapan informasi privat di ruang publik bisa berkonsekuensi hukum: pelanggaran data pribadi (UU Nomor 27 Tahun 2022). Selain itu, penyingkapan informasi di medsos kerap dibenturkan dengan perangkat hukum yang represif: UU ITE.
Selain itu, jika tak disertai kemampuan untuk memverifikasi setiap informasi, penyebaran informasi yang berujung viral di medsos bisa menjadi pembunuhan karakter atau perusakan reputasi (character assassination) untuk tertuduh yang tak bersalah.
Dan, yang cukup berbahaya, pendekatan “no viral, no justice” hanya akan menghadirkan penegakan hukum berbasiskan kasus-kasus yang viral di media sosial. Aparat penegak hukum hanya gerak cepat untuk kasus-kasus viral, tetapi tetap lamban dan korup dalam kasus-kasus yang tak terpantau oleh pengguna medsos. Ini juga berlaku pada isu sosial, politik, dan ekonomi.
Pendekatan “no viral, no justice” memang bisa mempercepat penegakan hukum untuk sebuah kasus, tetapi itu sangat kasuistik dan tak mengubah budaya korup dan birokratis lembaga penegak hukum.
Jadi, selain perlu bahu-membahu memviralkan sebuah kasus ketidakadilan di medsos, tentu saja dengan prinsip verifikasi informasi dan pengetahuan hukum yang memadai, perlu juga bahu-bahu memperjuangkan perombakan sistem dan lembaga penegakan hukum di Indonesia agar lebih melayani dan berkeadilan.