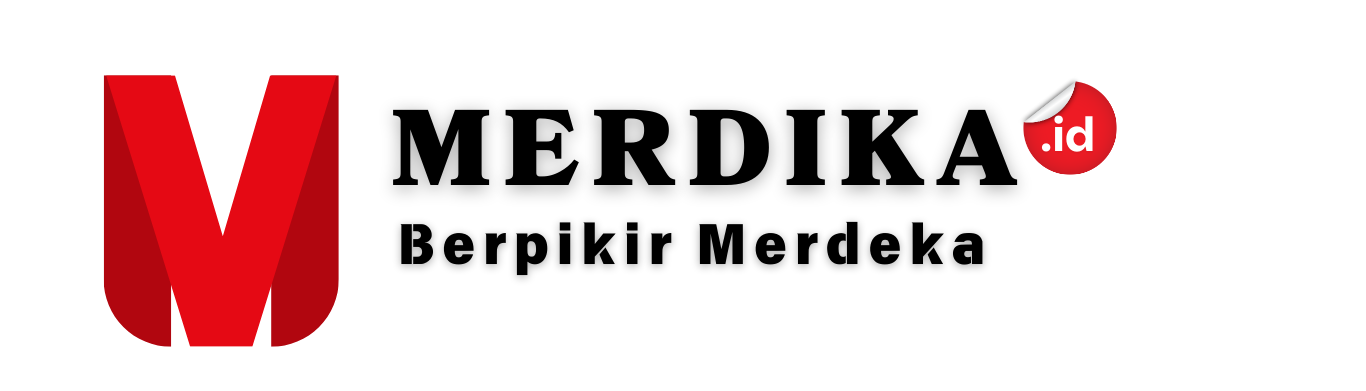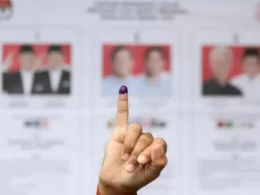Dulu, di pengujung tahun 90-an, kita pernah punya sebuah mimpi besar. Setelah puluhan tahun segalanya diatur dari Jakarta, angin reformasi membawa harapan bernama otonomi daerah.
Bayangan kita sederhana saja: kekuasaan yang lebih dekat dengan rakyat akan melahirkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. Otonomi daerah ibarat rumah impian yang mulai kita bangun di atas puing-puing sentralisme, sebuah janji bahwa setiap sudut negeri akan ikut merasakan nikmatnya kemerdekaan.
Hampir tiga dekade berlalu, dan kita terbangun pada kenyataan yang sedikit pahit. Rumah impian itu, alih-alih berdiri kokoh, justru retak di sana-sini. Alih-alih menjadi sumber kesejahteraan, otonomi daerah di banyak tempat justru menjadi panggung baru bagi korupsi dan politik dinasti. Ryaas Rasyid, sang arsitek otonomi daerah sendiri, dengan berat hati mengakui bahwa proyek raksasa ini nyaris gagal. Sungguh ironis sekali.
Otonomi daerah ibarat rumah yang hancur diterjang ombak sebelum selesai dibangun. Di mana letak kesalahannya? Kita bisa menunjuk banyak faktor, mulai dari regulasi yang tumpang tindih hingga tarik-menarik kepentingan elite pusat dan daerah. Namun, jika kita menatap lebih dalam, ada dua borok utama yang menggerogoti fondasi rumah ini dari dalam: minimnya pemimpin berkualitas dan rapuhnya partisipasi warga.

Krisis pemimpin berkualitas
Mari kita bicara tentang pemimpin. Untuk mendapatkan nakhoda yang mumpuni, kita merancang pilkada langsung sejak 2005. Niatnya mulia, biarlah rakyat yang memilih langsung. Namun, sistem ini ternyata membuka kotak pandora berbiaya fantastis.
Kajian Litbang Kemendagri pada 2023 memotret betapa mahalnya ongkos demokrasi ini: rata-rata Rp 30 miliar untuk menjadi bupati/wali kota, dan bisa mencapai Rp 100 miliar untuk kursi gubernur.
Dari mana uang sebanyak itu? Di sinilah para “cukong” atau donatur kaya raya masuk gelanggang. Mereka menyuntikkan dana, dan tentu saja, tidak ada makan siang gratis. Ketika jagoan mereka menang, tagihan datang dalam bentuk aneka kemudahan: prioritas proyek pengadaan, izin usaha, hingga perlindungan hukum. Akibatnya, seperti yang dianalisis oleh Hadiz (2010) dan Mietzner (2013), pilkada bukan lagi pertarungan gagasan, melainkan adu tebal dompet. Kemenangan tak lagi ditentukan oleh debat program, tapi oleh derasnya “serangan fajar”. Seorang mantan bupati di Jawa Tengah, dalam sebuah acara focus group discussion (FGD), bahkan hafal tarifnya per suara, dari yang terendah Rp 35 ribu di Purbalingga hingga Rp 500 ribu di Salatiga.
Lingkaran setan ini terbukti nyata. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa antara tahun 2004 hingga 2024, setidaknya 167 kepala daerah telah terjerat korupsi. Ironisnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sedikitnya 138 kandidat di pilkada 2024 yang rekam jejaknya bersinggungan dengan kasus korupsi.
Ini adalah buah dari sistem yang memaksa politisi terlibat dalam kesepakatan klientelistik dan menyuburkan oligarki, di mana kekayaan material dengan mudah diterjemahkan menjadi kekuasaan politik, persis seperti yang digambarkan oleh Winters (2011).

“Massa mengambang” dan partisipasi semu
Penyakit kedua adalah warisan dari masa lalu. Selama 32 tahun di bawah Orde Baru, kita sengaja dijadikan “massa mengambang” (floating mass): dijauhkan dari politik, tak terikat ideologi, dan buta soal gagasan. Bung Hatta jauh-jauh hari sudah mengingatkan, politik tanpa “keinsyafan” atau kesadaran hanya akan melahirkan manusia “pembebek” yang mudah digiring elite.
Konsekuensinya terasa hingga kini. Tanpa basis massa ideologis, kandidat harus membangun “tim sukses”-nya sendiri, yang sering kali direkrut dengan janji jabatan atau proyek. Inilah peta jalan menuju klientalisme dan nepotisme.
Di sisi lain, massa yang mengambang menjadi target empuk politik uang dan sentimen primordial. Partisipasi publik pun menjadi rapuh. Meskipun Kemendagri mencatat ada sekitar 570 ribu ormas pada 2024, sangat sedikit yang benar-benar independen dan kritis. Banyak yang jatuh menjadi “NGO Bodrex” yang hobi memeras atau “ormas plat merah” yang menjadi centeng penguasa lokal, sebuah fenomena yang dipotret oleh Berenschot (2018).
Kondisi ini diperparah oleh kegagalan pemekaran wilayah. Sejak 1999 hingga 2014, 223 daerah otonomi baru (DOB) lahir, sering kali karena desakan elite. Namun, evaluasi Kemendagri pada 2012 menyimpulkan 70 persen di antaranya gagal. Temuan BPK pun tak kalah mencemaskan: 443 dari 503 pemerintah daerah (sekitar 88 persen) berstatus belum mandiri secara fiskal dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

Menata ulang rumah kita
Haruskah kita menyerah dan merobohkan rumah ini? Tentu tidak. Otonomi daerah adalah keniscayaan bagi negeri kepulauan yang sangat beragam ini. Ini adalah jalan tanpa putar balik. Yang kita perlukan adalah perbaikan mendasar.
Pertama, desentralisasi asimetris. Kita harus berhenti memberlakukan kebijakan “satu ukuran untuk semua” (fit all-size). Setiap daerah unik. Daerah dengan tradisi musyawarah yang kuat seperti di Minangkabau atau komunitas adat lainnya bisa menerapkan model demokrasi yang sesuai dengan kearifan lokalnya, bukan dipaksa menelan mentah-mentah sistem pemilu liberal yang mahal.
Kedua, evaluasi DOB secara tegas. Moratorium pemekaran yang kini sesekali diwacanakan untuk dicabut harus dijalankan dengan pendekatan selektif. Aspirasi masyarakat memang penting, tetapi kelayakan ekonomi dan kapasitas daerah jauh lebih krusial. Opsi untuk menggabungkan kembali DOB yang gagal ke daerah induknya harus dipertimbangkan secara serius.
Ketiga, dan ini yang terpenting, membangkitkan partisipasi warga. Pemerintah harus proaktif menciptakan ruang bagi warga untuk terlibat, mulai dari penyusunan APBD hingga pengawasan proyek pembangunan. Di sisi lain, inisiatif dari bawah—forum warga atau komunitas—harus didorong agar bisa menjadi kekuatan penyeimbang yang efektif. Memberi ruang bagi partai politik lokal yang otentik juga bisa menjadi solusi agar agenda politik lebih membumi dan menyuarakan kepentingan nyata masyarakat setempat.
Mimpi otonomi daerah belum padam, ia hanya terluka dan butuh dirawat. Tugas kita bersama adalah menagih janji awalnya. Otonomi daerah bukan sekadar memindahkan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi memastikan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial benar-benar sampai ke depan pintu rumah setiap warga Indonesia.