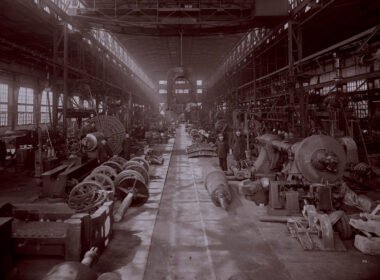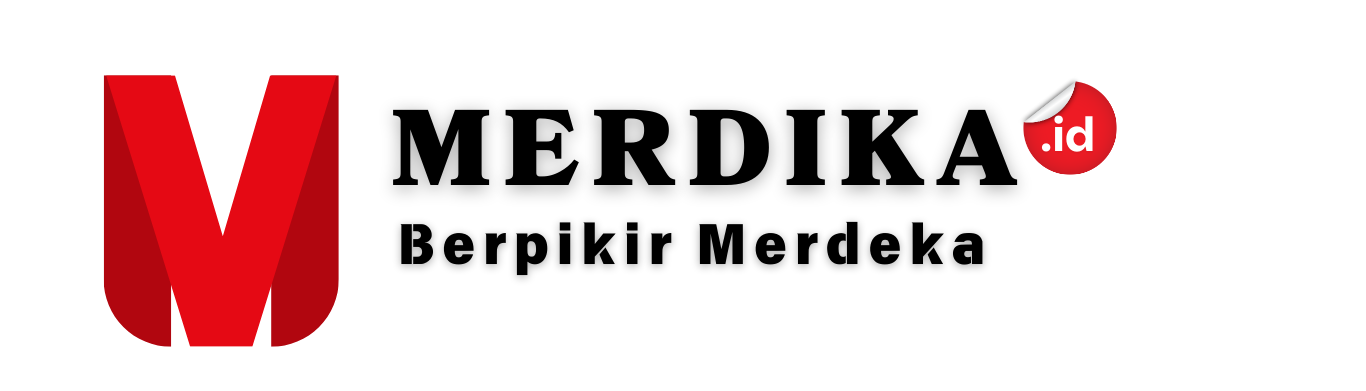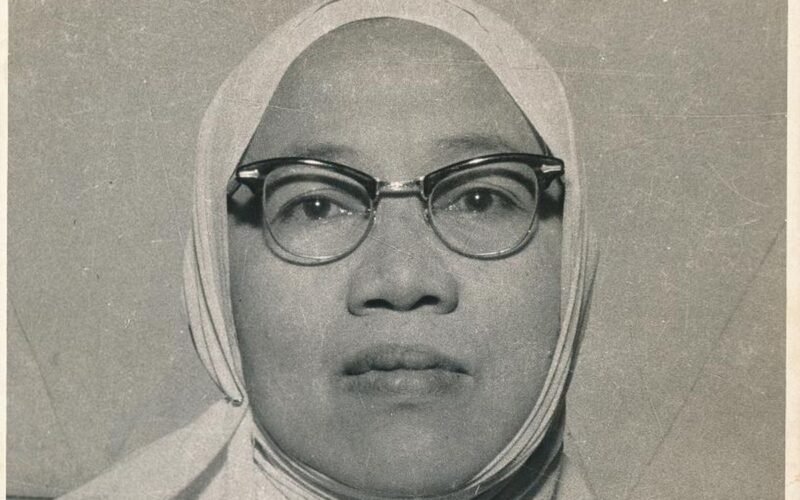Pertama kali Indonesia memiliki Kementerian Kebudayaan sejak merdeka 69 tahun silam, tetapi sepak terjang menterinya justru langsung meruntuhkan harapan masyarakat.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu, 2 Juli 2025, Fadli Zon, sang nakhoda Kementerian Kebudayaan, tetap kekeuh menyangkal peristiwa perkosaan massal dalam tragedi kerusuhan Mei 1998. Seperti batu keras yang menolak dihantam kenyataan, Fadli terus berlindung di balik perdebatan “perkosaan massal”.
Dengan argumentasi berbau fasistik, ia mengaitkan perkosaan massal dengan pembantaian skala besar yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Ia menyebut peristiwa pembantaian Nanjing di Tiongkok, pada 1937, yang mengorbankan 100 ribu hingga 200 ribu warga tak berdosa.
Pernyataan itu merupakan puncak kedangkalan intelektual seorang pejabat yang dipercaya memimpin Kementerian Kebudayaan.
Perdebatan definisi
Definisi yang disodorkan oleh Fadli Zon tidak relevan. Kejahatan kemanusiaan, seperti perkosaan massal, tidak diukur dari jumlah korban, melainkan oleh dua aspek: meluas (widespread) dan sistematis.
Padahal, jika benar Fadli Zon sudah pernah membaca hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, di situ terurai dengan jelas bahwa perkosaan itu terjadi secara meluas: Jakarta dan sekitarnya, Medan, dan Surabaya. Selain itu, kekerasan itu terjadi dalam rentang waktu yang hampir sama, dilakukan secara beramai-ramai (gang rape), dan mengarah pada etnis tertentu (Tionghoa).
Jika membaca kronologi atau testimoni yang disampaikan oleh para pendamping korban, ada pola umum dan mirip dalam rentetan kejadian itu. Jika semua cerita itu dirangkai menjadi satu, kita bisa mengendus adanya pola yang terorganisir.

Mengangkangi nilai-nilai kebudayaan
Cara pandang Fadli Zon, yang selalu mempertanyakan jumlah korban, jelas mengangkangi nilai-nilai kebudayaan: pengakuan atas martabat (dignity) dan kesakralan (sanctity) setiap individu. Harus diingat, peradaban dibangun di atas keyakinan bahwa setiap nyawa manusia berharga.
Argumentasi jumlah korban hanya mendehumanisasi korban. Seolah mereka yang menjadi korban, tidak punya hak hidup. Ini logika biadab dan tak berkebudayaan.
Di samping itu, cara pandang yang mempertanyakan jumlah korban, jelas mencoba mengaburkan kejahatan kemanusiaan. Padahal, sekalipun jumlahnya hanya sedikit, tetapi kejahatannya bersifat sistematis dan menyasar etnis tertentu. Hal itu bisa dibaca sebagai teror untuk menciptakan ketakutan dan subordinasi terhadap ras tertentu.
Sebagai Menteri Kebudayaan, Fadli Zon seharusnya belajar bahwa kebudayaan yang besar dan tangguh adalah kebudayaan yang mampu menghadapi babak kelam sejarahnya untuk belajar dan menyembuhkan diri.
Argumentasi jumlah korban adalah serangan langsung terhadap empati. Ia mengajarkan logika yang mengerikan: bahwa simpati dan kepedulian kita harus bersyarat dan berjenjang.
Pada akhirnya, menolak mengakui perkosaan massal Mei 1998 dengan dalih angka adalah tindakan anti-budaya. Itu adalah upaya untuk mengganti nilai luhur kemanusiaan, martabat, dan empati dengan kalkulasi politik yang kejam.
Menyangkal Pancasila
Mari kita camkan sila ke-2 dari Pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalimat ini sangat kaya makna. Pertama, pengakuan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat (inherent dignity) yang sama dan tak ternilai. Kemanusiaan adalah sebuah kualitas, bukan kuantitas.
Kedua, prinsip perlakuan yang adil. Bahwa tidak boleh ada manusia yang dibeda-bedakan. Semua harus diperlakukan setara sebagai anak bangsa dan mendapatkan kesamaan di depan hukum.
Bahwa kekerasan terhadap perempuan Tionghoa pada Mei 1998 adalah sebuah kesalahan sejarah yang melukai prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan karena itu, berdasarkan prinsip perlakuan yang adil, negara tak hanya harus mengakui kesalahan tersebut, tetapi juga mengusutnya hingga tuntas dan menyeret seluruh pelakunya ke pengadilan HAM.
Ketiga, penghormatan pada keberadaban. Beradab berarti mempunyai adab; budi pekerti, perilaku, sikap, maupun cara bertindak yang menjunjung tinggi kesopanan dan kemanusiaan. Dan perkosaan jelas bukan perbuatan beradab.
Argumentasi angka Fadli Zon jelas tidak beradab. Ia memperdebatkan kejahatan dengan angka. Padahal, mau sedikit atau banyak, semuanya adalah tindakan tak beradab dan menginjak nilai-nilai kemanusiaan.
Rekam jejak Fadli Zon
Melihat penyangkalan membatu Fadli Zon terhadap kasus perkosaan massal dalam tragedi Mei 1998, juga upayanya menutupi jejak kelam pelanggaran HAM di masa Orde Baru (Orba), seharusnya tak membuat kita kaget.
Rekam jejaknya memang menunjukkan bahwa dia adalah pendukung Orba dalam sejarah. Pada 1997-1998, berkat kedekatannya dengan rezim Orba, ia sudah menjabat anggota MPR. Jadi, pada saat terjadi gelombang pasang reformasi, ia adalah bagian dari kekuasaan.

Di sini perlu diklarifikasi bahwa Fadli Zon bukan aktivis 1998. Dia bukan pejuang reformasi. Tak setetes pun keringatnya menetes dalam gelora perjuangan yang diwarnai darah dan hilangnya nyawa mahasiswa dan rakyat itu. Justru sebaliknya, saat reformasi bergulir, ia berada satu selimut dengan Soeharto dan Cendana.
Foto Fadli Zon memegang pelantang suara, yang kerap disertai caption: aktivis, itu tidak terjadi pada 1997-1998. Foto itu diambil pada 1990-an (sekitar 1994-1995), saat dia masih menjadi pengurus Senat Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI).
Selain itu, sejak 1998 hingga seterusnya, ada banyak buku dan pernyataan Fadli Zon di media yang memang menyangkal perkosaan Mei 1998. Lewat buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” yang ia tulis pada 2004, Fadli Zon menyebut perkosaan massal sebagai peristiwa yang dibesar-besarkan.
Dalam wawancara dengan Far Easern Economic Review, Februari 1998, Fadli menggunakan frase “us” and “them” untuk mempertentangkan muslim dengan Tionghoa. Ia menyebut etnis Tionghoa sebagai biang kerok krisis ekonomi 1997-1998.
“Jika perlu, kami mundur 10 atau 15 tahun, mayoritas muslim sudah siap menghadapi tantangan apa pun, asalkan ada keadilan ekonomi. Kita bisa mulai membangun negara tanpa mereka (etnis Tionghoa),” katanya.
Pada Juli 1998, Asiaweek menerbitkan laporan investigasi berjudul “Ten Days That Shook Indonesia.” Banyak orang yang diwawancara, mulai dari relawan kemanusiaan hingga Fadli Zon. Di situ, Fadli membela Prabowo dan bilang bahwa ia (Prabowo) hanya “korban pembunuhan karakter”.
Itu hanya sebagian kecil, masih banyak rekam jejak dia sebagai loyalis dan pembela Orba. Dan hari ini, sebagai nakhoda Kementerian Kebudayaan, ia mendapatkan momentum dan kesempatan untuk menghapus dosa-dosa Orba dari sejarah Indonesia yang berkabut.
Dan karena itu, demi mencegah kerusakan lanjutan yang lebih meluas, mempertajam perpecahan bangsa dan merusak nilai-nilai Pancasila, Fadli Zon harus dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Kebudayaan.