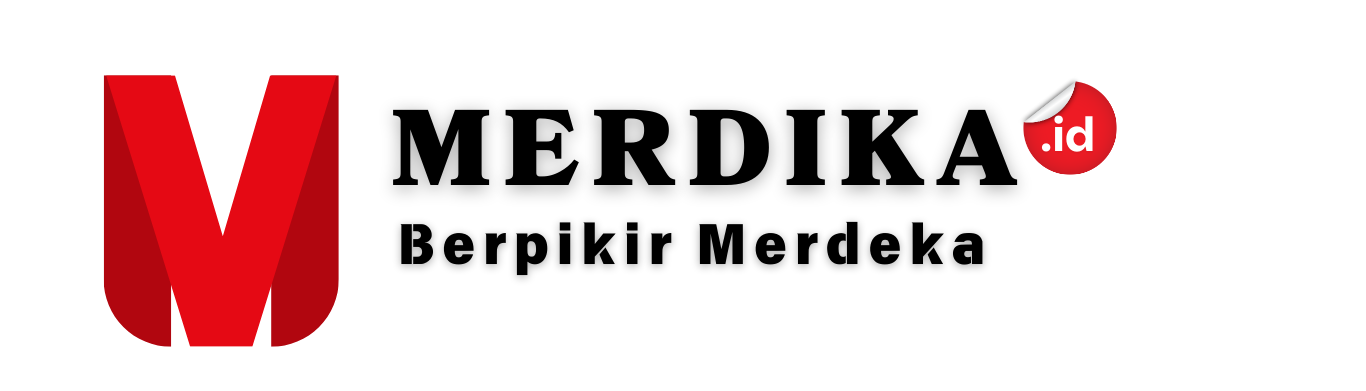Setiap peringatan Hari Kartini, kita kerap dihadapkan pada potret klasik Raden Ajeng Kartini—perempuan bangsawan Jawa dengan kebaya dan sanggul, simbol perjuangan perempuan untuk pendidikan dan kesetaraan.
Namun, di balik figur itu, ada sisi lain dari Kartini yang jarang diangkat ke permukaan, yakni relasinya dengan musik sebagai medium emosi, ekspresi kebudayaan, bahkan perlawanan terhadap tatanan patriarki kolonial.
Kartini hidup dalam dunia yang membatasi perempuan, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara kultural. Musik, bagi Kartini, bukan sekadar hiburan bangsawan, melainkan ruang intim tempat ia menemukan kebebasan batin. Dalam surat-suratnya kepada sahabat-sahabat korespondensinya di Eropa, Kartini kerap menyebut bagaimana musik klasik Eropa—terutama karya-karya Chopin dan Beethoven—mengusik hatinya, membangkitkan semangat, dan membantunya melawan keheningan sosial yang memenjara.
Pengalaman musikal Kartini memperlihatkan bahwa musik bisa menjadi jembatan lintas budaya, memperkaya imajinasi dan menyalakan gagasan-gagasan emansipatoris. Meski tumbuh dalam lingkungan feodal, ia menyalurkan semangat pembebasan melalui kata dan nada. Ia merindukan dunia yang lebih manusiawi, dan musik menjadi jendela untuk melihatnya.
Namun, ironisnya, warisan musikal Kartini jarang menjadi bagian dari narasi publik tentang dirinya.
Di tengah geliat industri musik modern hari ini, pelajaran dari Kartini menjadi relevan kembali. Musik bukan sekadar produk komersial atau alat populer, tetapi bisa menjadi medium pembentukan kesadaran. Generasi muda, khususnya perempuan, bisa melihat bagaimana Kartini menempatkan seni sebagai bentuk keberanian personal dan sosial. Dalam situasi sosial yang makin kompleks, musik bisa menjadi alat untuk menyuarakan keresahan, merayakan identitas, sekaligus menantang norma yang membatasi.

Sayangnya, kita telah terlalu lama membiarkan warisan ini menguap tanpa jejak. Bayangkan jika kita mengarsipkan secara serius relasi Kartini dengan musik—bukan hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga dalam karya musik baru yang diinspirasi dari surat-suratnya. Atau membayangkan festival musik tahunan yang mengangkat semangat emansipasi dan keadilan sosial ala Kartini, dengan melibatkan musisi perempuan dari berbagai latar.
Tentu generasi sekarang tak perlu meniru Kartini secara literal. Tetapi, kita bisa belajar dari caranya menjadikan kebudayaan, termasuk musik, sebagai bagian integral dari perjuangan hidup. Ia menulis, bermusik, dan berpikir dengan semangat zaman yang mendahului waktunya. Karena itu, penting untuk membebaskan narasi Kartini dari sekadar kisah pengorbanan menjadi kisah perlawanan yang kreatif dan penuh warna.
Kartini dan musik adalah dua entitas yang tidak terpisahkan dalam sejarah pergerakan perempuan Indonesia. Dari sinilah, kita bisa menggali ulang makna emansipasi: bukan hanya sebagai hak yang diperjuangkan, tetapi juga sebagai nyanyian yang harus terus kita lantunkan bersama. Sebab, seperti Kartini, kita pun butuh irama untuk melawan sepi dan mengubah dunia.
Sumber informasi:
Kartini, R.A. (1911). Habis Gelap Terbitlah Terang: Boeah Pikiran. Diterbitkan pertama kali oleh J.H. Abendanon, yang menyunting kumpulan surat Kartini kepada sahabat-sahabat korespondensinya di Eropa. Dalam beberapa surat kepada Estelle (Stella) Zeehandelaar dan Abendanon, Kartini menyebut kekagumannya pada musik Eropa seperti Chopin dan Beethoven, dan bagaimana musik mempengaruhi suasana batinnya.
Saskia Wieringa (1998). Kartini’s Letters and the Question of Women’s Rights in Indonesia, dalam Journal of Women’s History, Vol. 10 No. 3. Kajian ini menyoroti bagaimana Kartini menggunakan ekspresi budaya dan intelektual untuk menantang struktur patriarki dan kolonialisme. Musik disebut sebagai salah satu pengaruh batin yang memperkuat kesadaran Kartini.
Sulistyowati Irianto (2011). Musik, Perempuan dan Perubahan Sosial: Mencari Irama Emansipasi di Tengah Kultur Feodal. Makalah dalam Simposium Perempuan dan Kebudayaan yang menyinggung bagaimana peran seni, khususnya musik, menjadi instrumen yang memperkuat identitas dan kesadaran perempuan di masa Kartini dan setelahnya.
Anderson, Benedict. (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Versi Indonesia oleh Marjin Kiri. Dalam konteks Kartini, musik bisa dilihat sebagai bagian dari “komunitas terbayang” intelektual dan kebudayaan yang melintasi batas kolonial dan lokal, seperti dijelaskan Anderson dalam konsep nation sebagai komunitas budaya.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kumpulan Reproduksi Surat Kartini dan Arsip Pribadi J.H. Abendanon. Surat-surat asli Kartini yang banyak dikutip menunjukkan referensi terhadap selera musik dan perenungannya atas karya seni sebagai bagian dari kehidupan batin yang tertekan.
Rahmawati, Fitri. (2020). Emansipasi dan Ekspresi Diri: Kartini di Tengah Tradisi dan Modernitas. Artikel di Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 14, No. 2, membahas sisi lain Kartini sebagai perempuan modern awal yang memanfaatkan media ekspresi seperti surat dan musik sebagai bentuk perlawanan simbolik.