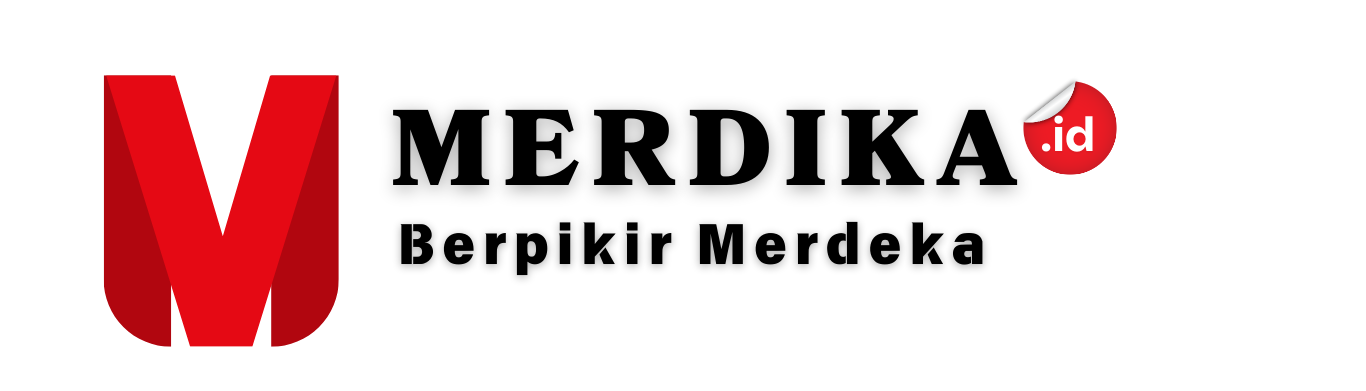Sejak resmi dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional pada 1964, lalu hari kelahirannya ditasbihkan sebagai hari besar nasional, sosok Kartini terus jadi bahan gugatan dan perdebatan. Dari ruang akademik sampai lini masa media sosial, Kartini dan perjuangannya terus menuai pro dan kontra.
Sayangnya, banyak penggugat Kartini, termasuk sejumlah sejarawan, melihatnya dengan kacamata kabur, tanpa berusaha memahami konteks sosial dan sejarah yang membentuknya. Akibatnya, “pengadilan sejarah” terhadap Kartini sering kali berjalan timpang, bahkan tendensius.
Pertama, Kartini dicemooh karena “hanya bisa curhat” lewat surat. Ia dianggap kalah gagah dibanding pejuang perempan lain yang mengangkat senjata, seperti Tjut Njak Dhien atau Martha Christina Tiahahu. Para pengkritik ini seolah menilai bahwa nilai seorang pejuang hanya bisa ditakar dari dentuman mesiu dan derap kaki pasukan.
Padahal, sejarah tidak sekadar mengenang siapa yang mengangkat senjata, tapi siapa yang menggerakkan kesadaran dan perlawanan. Kartini memilih pena, lalu menulis artikel dan melakukan korespondensi, sebetulnya ia menanam benih perubahan yang daya gaungnya jauh melampaui zamannya. Perjuangan sejati bukan soal alat yang digunakan, tapi daya dorongnya dalam membangkitkan cita-cita kolektif dan mendorong perubahan.
Cara pandang yang meletakkan narasi kepahlawanan identik dengan perjuangan bersenjata itu warisan Orde Baru (Orba). Narasi sejarah Orba menonjolkan peran tentara dan perjuangan bersenjata dalam revolusi nasional. Padahal, dalam perjuangan kemerdekaan hingga revolusi nasional (1945-1949), perjuangan dilakukan dengan berbagai cara: tulisan, diplomasi, pemogokan, demonstrasi, dan lain-lain. Kedaulatan RI diakui dunia, salah satunya juga via meja perundingan—bukan sekadar melalui perjuangan bersenjata.
Satu hal yang juga dilupakan para penggugat ini, bahwa saat Kartini mulai menggeliat dengan pikirannya, perlawanan bersenjata para bangsawan dan elite lokal sudah kalah semua: Aceh ditaklukkan pada 1904, serta Bali pada 1906. Jadi, perjuangan ala Kartini itu model baru, yaitu dengan gagasan dan tulisan. Tirto Adhisuryo dan Boedi Oetomo kemudian melengkapinya: berorganisasi.
Kedua, mereka yang mengecilkan Kartini juga seringkali menyepelekan arti penting sebuah ide. Sukarno dalam pidato pembukaan Konstituante 10 November 1956 bilang, sebuah bangsa hanya bisa bergerak karena ide besar yang membakar kesadaran rakyatnya.
“Hanya ide-lah yang bisa membuat manusia lemah merasa kuat dan berani,” ujar Sukarno. “Hanya ide yang membuat orang rela dibuang, rela masuk penjara, bahkan rela mati,” lanjutnya.
Jadi, apa arti penting ide Kartini?
Lewat surat-suratnya, Kartini meniupkan angin segar pemikiran modern. Ia tidak hanya bicara tentang emansipasi perempuan, tapi juga mendobrak tembok-tembok feodalisme, mengkritik kolonialisme, hingga menyerukan pentingnya pendidikan untuk membebaskan manusia. Dalam Jejak Langkah, Pramoedya Ananta Toer mencatat betapa kuat pengaruh Kartini terhadap Tirto Adhisuryo, sang pemula kebangkitan nasional.
Surat-surat Kartini tak hanya menginspirasi gerakan perempuan, tapi juga membekas dalam denyut nadi gerakan nasional (Saskia E. Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, 1999, hlm. 100). Sekolah perempuan yang ia dirikan melahirkan tokoh-tokoh penting, salah satunya RA Soekidjah Ranoodimedja, yang kelak terlibat dalam organisasi perempuan Istri Sedar dan turut berjuang dalam kemerdekaan. Dalam wawancara bersama Saskia Wieringa tahun 1983, Soekidjah menyebut dirinya sebagai “anak gerakan Kartini.”
Ide-ide Kartini, kalau kita jujur membaca, adalah yang paling maju di zamannya. Pram menyebutnya sebagai “pemula sejarah modern Indonesia”—perempuan yang pertama kali meletakkan pentingnya pendidikan sebagai senjata melawan penindasan dan kemunduran. Dan, ia bukan hanya bicara, tapi bertindak: mendirikan sekolah, menulis artikel, dan mengirim surat ke media. Semua itu pada masa ketika perempuan bahkan belum dianggap sebagai subjek berpikir.
Ketiga, tuduhan lain yang terus diulang adalah bahwa Kartini hanyalah proyek kolonial Belanda. Tuduhan ini sempat dilontarkan Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar, sejarawan senior Universitas Indonesia, yang menganggap Kartini adalah produk rekayasa sejarah.
Tapi Pramoedya Ananta Toer dengan tegas membantahnya dalam pengantar bukunya Panggil Aku Kartini Saja. Menurut Pram, tuduhan ini lahir dari anakronisme historis—kesalahan membaca tokoh di luar konteks zamannya.
Benar bahwa nasionalisme awal datang dari Barat, dan benar pula bahwa relasi tokoh-tokoh bumiputera dengan Eropa bukan hal asing. Tapi inilah tahap sejarah: pergaulan dengan Barat menjadi jembatan menuju kesadaran baru. Nasionalisme yang lahir dari relasi itu lama-lama berkembang menjadi gerakan pembebasan yang mandiri dan berakar.
Pertanyaan seperti “kenapa Kartini tidak mendirikan organisasi?” juga lahir dari cara pikir yang melupakan sejarah. Ketika Kartini menulis surat-suratnya, belum ada satu pun organisasi modern di Hindia. Masa organisasi baru dimulai pada 1906—dua tahun setelah Kartini wafat—dengan berdirinya Sarekat Prijaji oleh Tirto Adhisuryo, cikal bakal Sarekat Islam.
Kedekatan Kartini dengan J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan Hindia Belanda, juga bukan hal aneh. Banyak tokoh pergerakan lain juga punya patron dari kalangan kolonial. Tirto Adhi Soerjo dekat dengan Van Heutsz, Alimin dan Musso diasuh Prof. Dr. Hazeu, Haji Agus Salim punya relasi dengan Snouck Hurgronje, bahkan HOS Tjokroaminoto akrab dengan D.A. Rinkes.
Keempat, yang juga menyedihkan, Kartini sering dipersempit sebagai ikon feminisme sempit: sekadar pejuang hak perempuan. Padahal, kalau kita mau sungguh-sungguh membaca tulisannya, Kartini bicara lebih luas: dari kritik terhadap feodalisme, kolonialisme, agama yang membelenggu, hingga pendidikan, sastra, seni, teknik batik, jurnalisme, bahkan ketertarikannya pada teknologi modern.
Kartini bukan hanya pionir emansipasi perempuan, tapi juga pemikir besar yang menembus batas zamannya. Ia adalah suara zaman yang jauh mendahului kenyataan sosialnya. Perjuangannya tidak berakhir di buku sejarah atau kalender hari nasional—tapi terus hidup dalam perdebatan kita hari ini.
Kita harus meletakkan Kartini dan perjuangannya dalam konteks sejarahnya: sebuah zaman ketika Hindia-Belanda baru saja bersolek menuju liberalisasi dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi swasta untuk berinvestasi. Ketika pendidikan dan pers sedang menggeliat dan memberi panggung pada bangsa terjajah yang terdidik untuk mengekspresikan sikap dan kesadarannya pada zaman yang sedang bergerak.