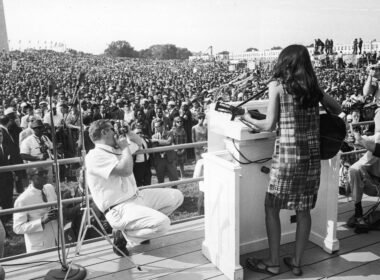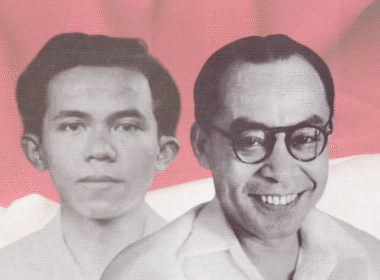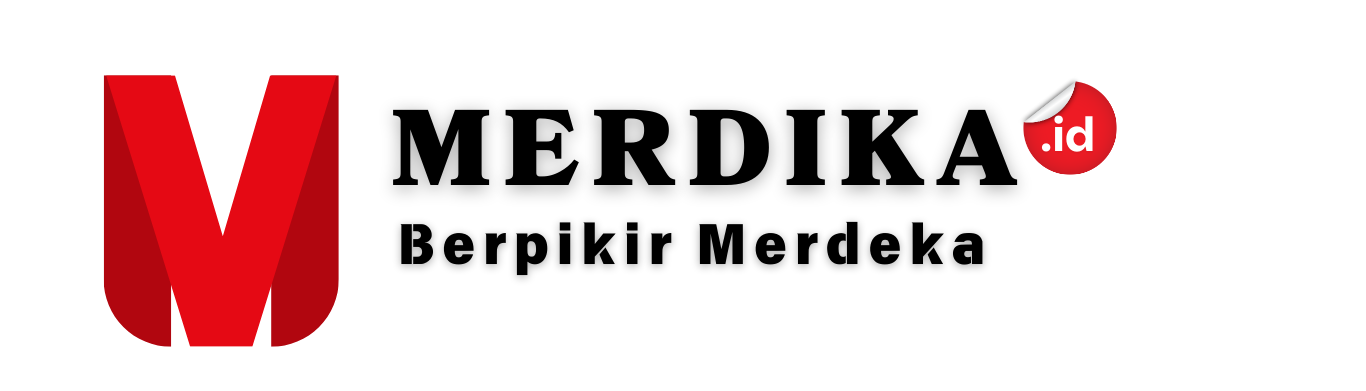May Day 2025 mengungkapkan dua wajah dalam satu momen: janji populis yang menyentuh, tetapi juga tangan besi terhadap suara yang lain. Janji manis Prabowo tentang kesejahteraan buruh berhadapan dengan kenyataan pahit—represifitas aparat yang mengekang kebebasan. Di tengah sorak-sorai lagu “Internasionale”, rakyat bertanya: apakah janji kesejahteraan untuk buruh akan benar-benar terlaksana ataukah sekedar janji politik berujung pahit seperti sebelum-sebelumnya.
Pada peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) 2025, rakyat menyaksikan paradoks yang sangat mencolok. Di satu sisi, di Lapangan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengumbar janji populis yang selama ini menjadi aspirasi kaum buruh, seperti pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), penghapusan outsourcing, serta mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dalam aksi itu Prabowo pun tampak mengepalkan tangan kiri ketika lagu Internasionale dikumandangkan. Sementara, di sisi lain, aksi buruh di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta dan di Semarang, Jawa Tengah, diwarnai tindakan represif brutal aparat keamanan menggunakan pentungan, water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Bahkan, aparat berpenampilan preman turut merangsek dan menghajar demonstran.

Fenomena ini mencerminkan pertentangan antara narasi keberpihakan kepada buruh/rakyat dan realitas antidemokrasi, hingga menimbulkan kekhawatiran besar atas pengabaian keadilan sosial di tengah dinamika politik Indonesia.
Dalam pidatonya yang berapi-api, Prabowo melontarkan serangkaian janji yang seolah menjadi jawaban atas keluhan buruh selama ini. Pembentukan DKBN, yang akan melibatkan tokoh buruh untuk memberikan masukan kebijakan, misalnya, diharapkan dapat memperbaiki regulasi ketenagakerjaan yang tidak pro-buruh. Penghapusan outsourcing, yang selama ini dikaitkan dengan ketidakpastian kerja, juga menjadi sorotan, meski Prabowo menegaskan perlunya mempertimbangkan kepentingan investor. Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam tiga bulan, pembentukan Undang-undang Pekerja Laut dan Perikanan, serta pengusulan Marsinah sebagai pahlawan nasional, semakin memperkuat citra keberpihakan kepada buruh. Bahkan, janji reformasi pajak dan pengesahan RUU Perampasan Aset menunjukkan ambisi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan korupsi, yang secara tidak langsung relevan bagi kesejahteraan buruh.
Namun, janji-janji ini, meski menggugah, tampak sarat nuansa retorika populis. Tanpa komitmen, kejelasan teknis, seperti anggaran, jadwal implementasi, atau mekanisme pengawasan, inisiatif ini berisiko menjadi retorika kosong.
Sebagai contoh, penghapusan outsourcing, yang disebut alih daya dalam regulasi Indonesia, adalah praktik bisnis yang sah selama mematuhi status hubungan kerja (PKWT atau PKWTT). Pernyataan penghapusan total tanpa strategi transisi yang jelas dapat mengganggu iklim investasi dan justru memicu pengangguran, alih-alih melindungi buruh. Selain itu, target pengesahan RUU dalam tiga bulan sulit dicapai mengingat proses legislasi di DPR sering terhambat oleh kepentingan politik. Narasi ini, meski membangkitkan harapan, tapi juga memunculkan skeptisisme: apakah janji ini benar-benar komitmen atau sekadar alat untuk meredam keresahan dan ketegangan sosial?
Krisis demokrasi di balik janji manis
Di tengah euforia janji Prabowo, aksi buruh pada May Day 2025 di Gedung DPR Senayan dan Semarang justru direspons dengan tindakan represif aparat keamanan. Penggunaan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa menunjukkan kontradiksi antara wacana pro-buruh dan realitas tindakan otoriter. Aksi brutal ini bukan hanya melukai fisik, tetapi juga menciderai semangat demokrasi, di mana hak untuk menyuarakan aspirasi melalui aksi damai seharusnya dilindungi.
Kekerasan aparat ini mempertegas krisis demokrasi yang lebih luas, sebagaimana tercermin dari pola militerisasi dalam kebijakan pemerintahan Prabowo. Misalnya, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 yang memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan dan TNI untuk mengelola kawasan hutan, sementara Babinsa dikerahkan untuk “menjaga kelestarian hutan”, yang lebih terasa sebagai ekspansi proyek ketimbang konservasi. Pola ini menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk mengandalkan pendekatan keamanan dalam menangani isu sosial, termasuk protes buruh, alih-alih dialog demokratis.
Tindakan represif ini juga mengingatkan catatan kelam Orde Baru, di mana buruh, termasuk Marsinah, menjadi korban represi negara. Ironisnya, usulan menjadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional justru berlangsung di tengah praktik yang mengingatkan pada era otoritarianisme. Perlu diwaspadai pengakuan ini akan dibarter dengan pengakukan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Jika ini terjadi, sejatinya merupakan penghinaan terhadap nilai perjuangan buruh. Para pimpinan serikat buruh harus kritis dan tak boleh terlena pada efuoria ini.
Paradoks May Day 2025 mencerminkan ketegangan struktural dalam pemerintahan Prabowo: keinginan untuk tampil sebagai pemimpin pro-rakyat, berhadapan dengan kecenderungan otoriter yang mengakar dalam pendekatan keamanan. Janji-janji populis, meski membangkitkan harapan, berisiko kehilangan legitimasi jika tidak diwujudkan melalui kebijakan konkret dan transparan. Di sisi lain, tindakan represif aparat menunjukkan bahwa ruang demokrasi untuk menyuarakan aspirasi masih terbatas, bertentangan dengan semangat Pancasila yang menjunjung musyawarah dan keadilan sosial.
Untuk mengatasi paradoks ini, pemerintah perlu mengambil langkah konkret:
Pertama, merumuskan rencana aksi yang jelas untuk setiap janji, dengan indikator keberhasilan dan mekanisme akuntabilitas.
Kedua, alih-alih membentuk DKBN, negara lebih baik membangun Komisi Nasional Hubungan Industrial yang melibatkan buruh, pengusaha, dan pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur penegak hukum untuk menyusun kebijakan hubungan industrial yang pro penguatan industri nasional dan kesejahteraan buruh, serta mengembangkan mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan konflik secara damai.
Ketiga, mereformasi pendekatan keamanan (security approach) dengan memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan aksi massa. Tanpa langkah ini, euforia May Day 2025 hanya akan menjadi ilusi, sementara buruh terus berjuang di tengah represi dan ketidakpastian.
Dan, yang harus diingat, untuk mewujudkan visi bersama Indonesia Maju, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah harus melampaui retorika populis serta memastikan bahwa hak buruh dihormati, baik dalam kebijakan maupun dalam praktik di lapangan. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat keluar dari paradoks ini dan menuju hubungan industrial yang benar-benar harmonis dan adil.