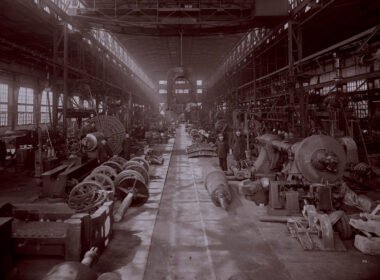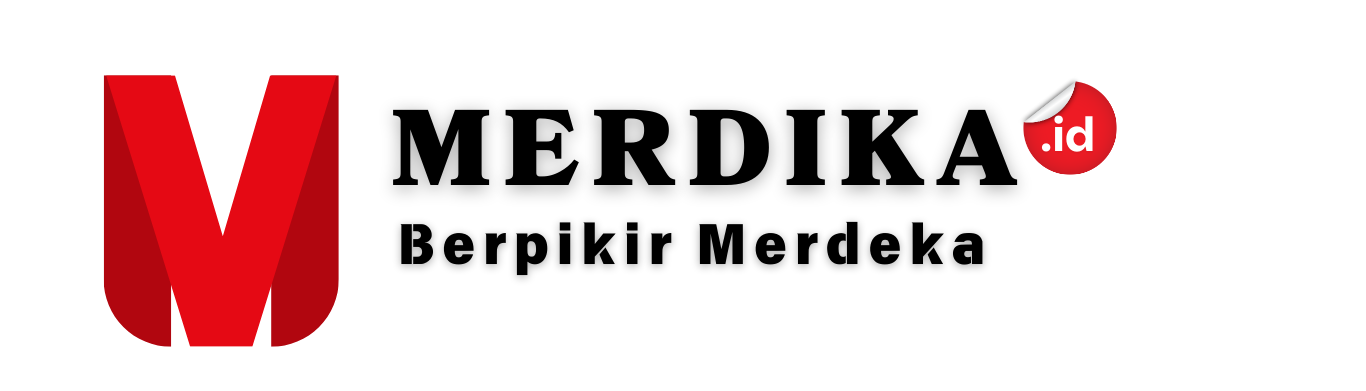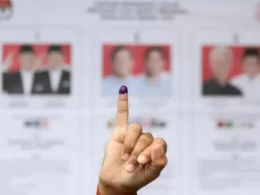Agenda reformasi, selain menumbangkan Orde Baru juga mengembalikan demokrasi ke tangan rakyat. Setelah 32 tahun pemerintahan dikuasai oleh oligarki Soeharto dengan sokongan kroni militer dan bisnis, banyak terjadi pelanggaran HAM, perampasan hak atas hidup, dan semakin tersentralnya pundi-pundi kekayaan melalui ekstraksi sumber daya alam ke kantong sang oligark bersama kroninya.
Salah satu agenda utama reformasi pasca-kejatuhan Soeharto pada 1998 adalah reformasi militer di Indonesia. Reformasi ini bertujuan untuk mengakhiri dominasi militer dalam politik dan pemerintahan sipil, yang telah berlangsung sejak era Orde Baru melalui doktrin dwifungsi ABRI. Melalui serangkaian kebijakan, seperti pemisahan TNI dan Polri serta penghapusan kursi militer di DPR/MPR, Indonesia berupaya membangun supremasi sipil dalam tata kelola negara.
Akan tetapi, sejak 2022 hingga saat ini wacana revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi ancaman atas kembalinya militer ke ranah sipil. Jika revisi ini disahkan, maka akan menggagalkan agenda reformasi yang telah berlangsung selama dua dekade.
Dengan kata lain, revisi ini akan mengembalikan posisi militer dalam politik, sehingga memungkinkan mereka untuk kembali menduduki posisi strategis di pemerintahan sipil. Kondisi tersebut menyiratkan sebuah pesan bahwa kewenangan tanpa batas yang menjadi semangat reformasi 1998 berisiko diaktifkan kembali.
Kronologi reformasi militer
Reformasi militer di Indonesia berlangsung dalam beberapa fase yang mencerminkan dinamika hubungan antara militer dan sipil. Pada tahap awal (1998-2001), reformasi berfokus pada pembongkaran struktur dwifungsi ABRI yang selama Orde Baru memberikan militer peran ganda dalam pertahanan dan politik. Namun, perjalanan reformasi ini mengalami berbagai tantangan, mulai dari resistensi internal hingga kebijakan politik yang menghambat perubahan struktural, yang terlukis pada tahap reformasi stagnan (2001-2004); dan reformasi parsial (2004-sekarang).
Reformasi awal (1998-2001), pada periode ini, ditandai dengan langkah-langkah drastis untuk membatasi keterlibatan militer dalam politik dan pemerintahan sipil. Salah satu pencapaian utamanya adalah penghapusan formal dwifungsi ABRI serta pemisahan Polri dari TNI. Saat itu, Presiden Abdurrahman Wahid mencoba melakukan upaya radikal untuk membatasi pengaruh militer, tetapi mendapatkan perlawanan dari faksi konservatif dalam tubuh TNI. Perlawanan ini berkontribusi pada ketegangan politik yang berujung pada pemakzulannya pada tahun 2001 (Mietzner, 2006).
Reformasi stagnan (2001–2004), fase ini terjadi pada kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, di mana reformasi militer mengalami stagnasi. Militer mulai mendapatkan kembali pengaruhnya dalam politik, dan struktur komando teritorial tetap dipertahankan (Anwar, 2001). Keberlanjutan sistem ini memungkinkan TNI tetap memiliki kendali atas wilayah-wilayah strategis, memperlambat agenda reformasi yang bertujuan untuk membatasi intervensi militer dalam pemerintahan sipil.
Reformasi parsial (2004-saat ini), dimulai pada era kepeminpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana reformasi militer berlanjut dengan pendekatan yang lebih moderat. Di era ini struktur komando teritorial dan bisnis militer tetap tidak tersentuh (Mietzner, 2006), dan menunjukkan bahwa reformasi hanya berjalan secara parsial.
Lalu, kondisi semakin buruk saat Presiden Joko Widodo berkuasa. Hal ini terjadi pada akhir periode kedua kepeemimpinannya, yakni 2023, sebelum pemilihan presiden. Revisi Undang-Undang TNI kembali dimunculkan. Wacana revisi Undang-Undang TNI kembali memunculkan kekhawatiran akan kembalinya militer ke ranah sipil, yang berpotensi menggagalkan kemajuan reformasi yang telah dicapai selama lebih dari dua dekade.
Ancaman atas revisi UU TNI
Pengesahan revisi Undang-Undang TNI dapat membawa sejumlah permasalahan serius, karena akan berdampak pada rusaknya tatanan demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Revisi ini berpotensi mengembalikan pengaruh militer dalam pemerintahan sipil, membuka peluang bisnis bagi TNI, serta melemahkan akuntabilitas hukum bagi personel militer. Akibatnya, dampak dari perubahan ini tidak hanya menghambat reformasi militer yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, tetapi juga memperbesar risiko pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan.
Revisi Pasal 47 ayat (2) memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga tanpa batasan yang jelas (Amnesty International Indonesia, 2025). Ketentuan ini membuka peluang bagi militer untuk kembali mendominasi birokrasi sipil, mengancam prinsip supremasi sipil yang menjadi pilar utama demokrasi (Mietzner, 2006). Dengan semakin banyaknya perwira aktif yang mengisi posisi strategis dalam pemerintahan, kontrol sipil atas militer dapat semakin melemah, serta menciptakan potensi penyalahgunaan kekuasaan tanpa mekanisme pengawasan yang efektif.
Salah satu poin revisi yang paling berbahaya adalah usulan penghapusan larangan berbisnis bagi anggota TNI, yang mencerminkan kemunduran dalam reformasi militer (Amnesty International Indonesia, 2025). Keterlibatan militer dalam bisnis tidak hanya berpotensi memperburuk praktik korupsi, tetapi juga menciptakan konflik kepentingan yang dapat mengancam transparansi pemerintahan. Dalam sejarahnya, militer yang terlibat dalam kegiatan ekonomi cenderung lebih sulit diawasi dan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok (Mietzner, 2006).
Revisi Pasal 65 ayat (2) memperkuat yurisdiksi peradilan militer atas semua pelanggaran yang dilakukan prajurit, termasuk saat mereka menduduki jabatan sipil (Amnesty International Indonesia, 2025). Hal ini bertentangan dengan prinsip “equality before the law” dan berpotensi memperkuat impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Anwar, 2001). Dengan dikecualikannya personel TNI dari peradilan umum, upaya penegakan hukum menjadi tidak seimbang dan dapat memperburuk ketidakadilan dalam sistem hukum nasional.
Singkat kata, upaya menghidupkan kembali peran TNI dalam ranah sipil dan kenegaraan, melalui revisi UU TNI merupakan langkah mundur yang dapat mengancam demokrasi Indonesia. Melalui pengesahan revisi ini, militer akan kembali terlibat dalam politik dan pemerintahan sipil, melemahkan prinsip supremasi sipil yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.
Selain itu, revisi akan membuka peluang kembali militer untik berbisnis. Dampak dari pemberian keleluasaan untuk berbisnis tersebut akan memperparah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mengingat minimnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap institusi militer.
Lebih dari itu, revisi ini juga berisiko melemahkan akuntabilitas hukum bagi prajurit TNI. Dengan penguatan yurisdiksi peradilan militer, pelanggaran yang dilakukan oleh personel TNI, termasuk yang menduduki jabatan sipil, tidak akan dapat diadili dalam sistem peradilan umum. Hal ini berpotensi meningkatkan impunitas dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia dan menghambat upaya penegakan hukum yang adil serta transparan.
Ketimbang mengesahkan UU TNI, mestinya DPR dan pemerintah lebih berfokus pada agenda reformasi militer yang masih tertunda, seperti pembentukan UU Tugas Perbantuan, reformasi sistem peradilan militer, serta restrukturisasi komando teritorial. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam jalur demokratis yang menjunjung tinggi supremasi sipil serta profesionalisme militer.
Referensi:
Amnesty Internasional Indonesia. 6 Maret 2024. Siaran Pers: Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI yang Menghidupkan Dwifungsi. Diakses dari https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-pembahasan-revisi-undang-undang-tni-yang-menghidupkan-dwifungsi/03/2025/
Anwar, D.F., 2001. Negotiating and consolidating democratic civilian control of the Indonesian military. East-West Center Occasional Papers Politics and Security Series. Diakses dari scholarspace.manoa.hawaii.edu
Mietzner, M., 2006. The politics of military reform in post-Suharto Indonesia: Elite conflict, nationalism, and institutional resistance. East West Center Washington. Diakses dari https://www.eastwestcenter.org/publications/politics-military-reform-post-suharto-indonesia-elite-conflict-nationalism-and-institut