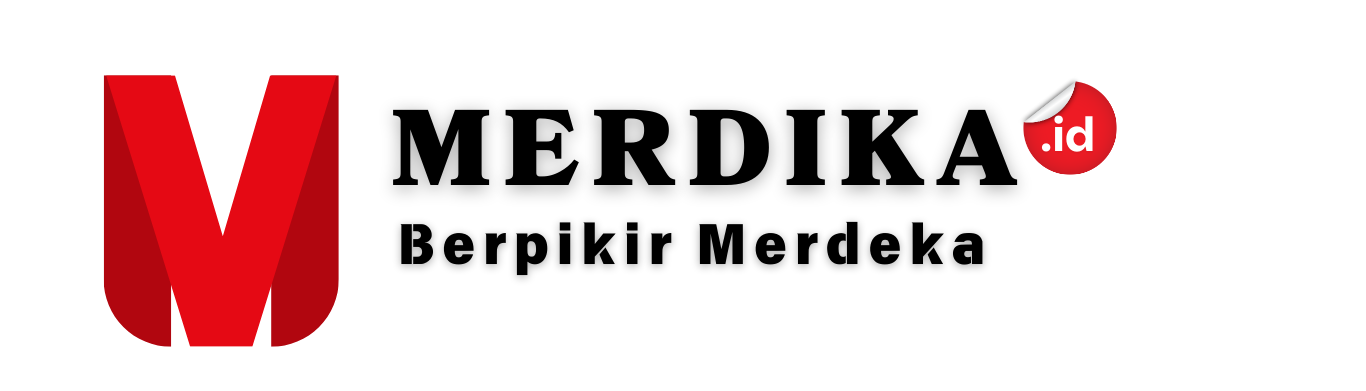Di Sabtu malam Paskah tahun ini, sebuah pesan khotbah menggema dari mimbar gereja: ras terkuat di bumi adalah perempuan.
Pernyataan ini bukan sekadar pujian kosong, tapi bersumber dari kisah Injil yang mencatat bahwa perempuanlah yang pertama kali mengetahui kebangkitan Yesus. Mereka yang pertama menyaksikan makam kosong, pertama mendengar kabar dari malaikat, dan pertama menyampaikan berita besar itu pada para rasul. Namun ironisnya, suara mereka dianggap tak layak dipercaya—hanya karena perempuan. Sungguh, sebuah gambaran getir tentang sejarah panjang pengabaian suara perempuan oleh budaya patriarkis.
Peringatan Hari Kartini tahun ini seolah menemukan gema baru dalam kisah tersebut. Kartini, seperti Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya di masa Yesus, menyampaikan sesuatu yang besar di tengah dunia yang belum siap mendengarkan. Ia bicara tentang pendidikan, emansipasi, dan kesetaraan—di saat Jawa masih memenjarakan perempuan di balik dinding keraton dan rumah adat. Pesannya sederhana: perempuan bukan makhluk nomor dua. Tapi hingga kini, gema suara itu masih berulang kali ditepis, dicurigai, atau dipolitisasi.
Apa yang terjadi pada perempuan pertama di pagi Paskah dan apa yang dialami Kartini di pengujung abad ke-19 adalah cermin dari struktur yang belum berubah sepenuhnya. Kita masih hidup dalam dunia yang sulit mempercayai perempuan: baik sebagai pemimpin, pembawa pesan, maupun pembawa perubahan. Ketika perempuan bicara tentang kebenaran—entah itu tentang kebangkitan, pelecehan, hak reproduksi, atau keadilan ekonomi—masih banyak yang merespons dengan keraguan, sinisme, bahkan kekerasan simbolik.
Namun justru di situlah letak kekuatan perempuan. Sejarah menunjukkan bahwa perempuan tidak menunggu diundang untuk berbicara. Mereka menerobos, membawa kabar, bahkan ketika dunia menutup telinga. Dalam konteks Indonesia modern, kita menyaksikan bagaimana perempuan memimpin gerakan lingkungan, memelopori pendidikan komunitas, membangun koperasi, hingga duduk di parlemen dan ruang-ruang pengambilan keputusan. Tapi seperti para perempuan di pagi Paskah, keberadaan mereka kerap diabaikan dalam narasi besar bangsa.
Hari Kartini tidak semestinya menjadi perayaan kosmetik tentang kebaya dan lomba merangkai bunga. Hari ini adalah momentum untuk mengingat betapa lama dan beratnya perjuangan perempuan agar suaranya didengar.
Dalam semangat Paskah—yang bicara tentang kebangkitan dari kematian, harapan dari kehancuran—kita diajak merenung: siapa yang hari ini sedang menyampaikan pesan penting, tapi tak kita dengarkan hanya karena ia perempuan.
Bangkitnya Yesus adalah pesan transformatif, dan Tuhan memilih perempuan untuk menyampaikannya pertama kali. Bukankah ini juga teguran keras bagi kita yang masih membatasi ruang perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan spiritual? Jika Tuhan saja mempercayakan kabar terbesar dalam sejarah iman kepada perempuan, mengapa kita masih ragu untuk mempercayakan kepemimpinan bangsa kepada mereka?
Perempuan bukan hanya objek yang perlu “diberdayakan”—mereka sudah berdaya. Yang perlu diubah adalah struktur dan budaya yang masih mendiskreditkan daya itu. Mulai dari ruang kerja yang bias gender, politik elektoral yang maskulin, hingga tafsir keagamaan yang membatasi ruang gerak perempuan. Kita tidak kekurangan Kartini baru—yang kurang adalah telinga yang bersedia mendengar dan sistem yang bersedia menerima perubahan.
Paskah dan Hari Kartini, meski berasal dari tradisi yang berbeda, namun sama-sama bicara tentang pembebasan dan kebangkitan. Maka mari kita rayakan keduanya bukan hanya dengan simbol, tetapi dengan aksi nyata. Aksi untuk memastikan bahwa suara perempuan—dari desa sampai parlemen, dari altar sampai ruang publik—didengar dan dihargai. Karena seperti pesan Paskah itu sendiri: kebangkitan tidak bisa dihentikan, apalagi jika dibawa oleh perempuan.
Di tengah dunia yang sering kali gelap dan menolak perubahan, perempuan datang membawa terang. Mereka bukan hanya menyampaikan kabar baik. Mereka adalah kabar baik itu sendiri.
Selamat Paskah dan Hari Kartini!